Periode Kolonial Inggris di Indonesia: Sebuah Interlude Sejarah yang Terlupakan
3 Nov 2025
Pendahuluan
Ketika kita berbicara tentang sejarah kolonial Indonesia, dua nama besar selalu mendominasi: Portugis sebagai pelopor dan Belanda sebagai penguasa terlama. Namun, ada satu periode singkat namun penting yang sering terlupakan dalam narasi sejarah kita, yaitu periode kolonial Inggris di Indonesia. Meskipun hanya berlangsung lima tahun (1811-1816), interlude Inggris ini membawa perubahan signifikan yang pengaruhnya masih terasa hingga hari ini.
Periode ini bukan sekadar perpindahan kekuasaan dari satu bangsa Eropa ke bangsa Eropa lainnya. Ini adalah masa yang penuh dengan eksperimen politik, reformasi ekonomi, konflik militer, dan pertukaran budaya yang intens. Di bawah kepemimpinan Thomas Stamford Raffles, seorang administrator kolonial yang visioner dan kontroversial, Indonesia mengalami transformasi kebijakan yang radikal berbeda dari sistem VOC Belanda yang telah mapan selama berabad-abad.
Saya akan mengajak Anda menelusuri periode yang menarik ini, dari kontak awal Inggris dengan Nusantara pada abad ke-16, klimaks penaklukan Jawa tahun 1811, eksperimen reformasi Raffles, hingga penyerahan kembali kepada Belanda tahun 1816. Mari kita gali bagaimana lima tahun singkat ini meninggalkan jejak yang masih bisa kita rasakan dalam struktur administrasi, warisan budaya, dan bahkan dalam cara kita memahami identitas nasional Indonesia.
Garis Waktu Sejarah: Dari Kontak Awal hingga Penyerahan Kembali
Kontak Awal Inggris dan Rivalitas dengan Belanda (Abad ke-16 hingga ke-18)

Minat Inggris terhadap Nusantara sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum penaklukan Jawa tahun 1811. Pada tahun 1579, pelaut dan bajak laut Inggris terkenal Sir Francis Drake mengunjungi Maluku (Kepulauan Rempah), menandai salah satu kontak pertama Inggris dengan wilayah yang kini menjadi Indonesia. Kunjungan Drake ini bukan sekadar eksplorasi, melainkan bagian dari strategi Inggris untuk menantang monopoli Portugis dan kemudian Belanda atas perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan.
Pada tahun 1601, Perusahaan Hindia Timur Inggris atau English East India Company (EIC) mendirikan pos perdagangan di Banten (Banten) di Jawa Barat. Banten pada masa itu adalah pelabuhan penting untuk perdagangan lada dan rempah-rempah lainnya. Namun, persaingan sengit dengan Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) Belanda segera membayangi. Belanda, yang telah mendominasi wilayah tersebut, tidak senang dengan kehadiran Inggris.
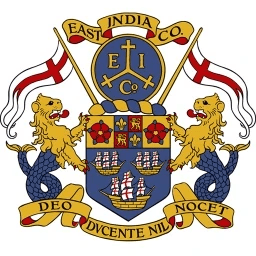
Konflik mencapai puncaknya pada tahun 1623 dalam peristiwa yang dikenal sebagai Pembantaian Amboyna. Di Pulau Ambon, Belanda menangkap dan mengeksekusi sepuluh pedagang Inggris dengan tuduhan (yang kemungkinan besar dibuat-buat) pengkhianatan. Peristiwa berdarah ini meracuni hubungan Anglo-Belanda dan secara efektif mengusir Inggris dari pulau-pulau rempah-rempah selama beberapa dekade. Pada tahun 1683, Inggris menutup pos Banten mereka di bawah tekanan Belanda, mengalihkan fokus mereka ke anak benua India dan perdagangan lainnya.
Meskipun mengalami kemunduran, Inggris terus mencari pijakan di Nusantara. Pada tahun 1685, EIC mendirikan pemukiman di pantai barat Sumatra di Bencoolen (Bengkulu) untuk memanfaatkan perdagangan lada yang menguntungkan. Mereka membangun Benteng Marlborough di sana pada tahun 1714 sebagai benteng kehadiran Inggris. Sementara itu, rivalitas Anglo-Belanda terus berlanjut. Selama Perang Anglo-Belanda Kedua, Inggris sempat mengamankan pulau Banda kecil Run, sumber pala, tetapi akhirnya menyerahkannya kepada Belanda.
Di bawah Perjanjian Breda (1667), Inggris setuju untuk melepaskan Run sebagai ganti koloni Belanda New Amsterdam (Manhattan), mengkonsolidasikan kontrol Belanda atas pulau-pulau rempah-rempah. Ini adalah kesepakatan yang mengubah peta dunia: Inggris mendapat New York, Belanda menguasai monopoli rempah-rempah Nusantara. Pada abad ke-18, ambisi Inggris di wilayah yang sekarang Indonesia sebagian besar terbatas pada pijakan kecil ini seperti Bencoolen, sementara Belanda mendominasi Jawa dan pulau-pulau luar.
Keterlibatan Inggris Selama Perang Napoleon (1800-1811)
Akhir abad ke-18 membawa peluang baru bagi Inggris. VOC bangkrut pada tahun 1799, dan Belanda jatuh di bawah kendali Napoleon Prancis (Kerajaan Holland di bawah saudara Napoleon) pada tahun 1806. Dengan Belanda menjadi sekutu Prancis, Inggris yang saat itu berperang melawan Napoleon Prancis menargetkan koloni-koloni Belanda.
Pada tahun 1795 dan lagi pada awal tahun 1800-an, pasukan Inggris merebut pos-pos Belanda di wilayah tersebut (sering kali dengan persetujuan pangeran Belanda yang diasingkan) untuk mencegah mereka membantu Prancis. Dorongan besar datang pada tahun 1810-1811: di bawah perintah Lord Minto (Gubernur Jenderal India Britania), Inggris melancarkan kampanye untuk mengambil Kepulauan Rempah dan Jawa.

gambar dari lord minto
Pada awal 1810, pasukan Inggris telah merebut pulau-pulau rempah-rempah kunci Ambon, Banda (Banda Neira), dan Ternate, memberikan pukulan besar bagi kekuatan Franco-Belanda di Hindia Timur. Kemenangan ini tidak hanya melemahkan cengkeraman Belanda-Prancis tetapi juga memberi Inggris akses langsung ke komoditas berharga seperti pala dan cengkeh.
Pada pertengahan 1811, Inggris beralih ke Jawa, pusat administratif Hindia Timur Belanda. Pada Agustus 1811, pasukan ekspedisi Inggris yang terdiri dari 10.000 orang, sebagian besar terdiri dari pasukan sepoy India dari Bengal dan Madras, mendarat di Jawa untuk mengusir rezim Franco-Belanda. Kampanye berlangsung cepat dan efisien.
Pasukan Inggris mendarat di dekat Batavia (Jakarta) pada 4 Agustus 1811 dan dengan cepat menduduki kota tersebut. Pada akhir Agustus, mereka menyerbu benteng Belanda yang tangguh di Meester Cornelis (Jatinegara), secara menentukan mengalahkan pasukan Franco-Belanda Gubernur Jenderal Jan Willem Janssens. Tentara kolonial Belanda menderita korban berat dalam kampanye enam minggu, dan pada September 1811 Jawa sepenuhnya berada di bawah kendali Inggris.
Lord Minto yang menang menunjuk anak didiknya Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur Jawa dan dependensinya pada 11 September 1811. Pada usia 30 tahun, Raffles sekarang secara efektif memerintah "kekaisaran kepulauan" dari beberapa juta penduduk, termasuk Jawa dan bekas kepemilikan Belanda lainnya.
Administrasi Inggris (1811-1816) dan Peristiwa Kunci

gambar dari sir stamford raffles (sumber: https://artandthecountryhouse.com/)
Periode 1811-1816 sering disebut sebagai interregnum Inggris di Indonesia. Raffles memerintah Jawa dari ibu kota di Batavia (dan kediaman negaranya di Buitenzorg, sekarang Bogor). Dia juga memegang kekuasaan atas bagian lain dari bekas Hindia Timur Belanda yang masih di tangan Inggris.
Raffles segera melakukan reformasi signifikan yang bertujuan mengubah sistem kolonial Belanda. Pemerintahan Inggris menghadapi beberapa perlawanan dan harus mengamankan otoritasnya melalui diplomasi dan kekuatan. Pada Juni 1812, mencurigai bahwa Kesultanan Yogyakarta yang kuat mungkin memberontak, Raffles melancarkan serangan preemptif.
Pasukan Inggris sebanyak 1.200 orang menyerang dan merebut Kraton (istana) Yogyakarta pada 20 Juni 1812. Serangan tersebut mengejutkan efektif: istana kerajaan dikuasai dalam satu hari, kota dijarah dan dijarah, dan Sultan Hamengkubuwono II digulingkan dan diasingkan. Ini adalah pertama kalinya istana Jawa jatuh ke tangan tentara Barat, sebuah pukulan yang sangat memalukan bagi prestise Jawa.
Inggris menyita perbendaharaan dan arsip kesultanan. Raffles bahkan mengirim kembali ke Inggris banyak dokumen dan artefak dari kraton sebagai trofi perang. Serangan brutal ini mengirim pesan yang jelas kepada penguasa Jawa lainnya bahwa pemberontakan akan dihancurkan tanpa ampun.
Di tempat lain, Inggris bergerak untuk mengamankan area strategis lainnya. Pada awal 1812, Raffles mengirim ekspedisi ke Palembang di Sumatra timur, setelah Sultan Mahmud Badaruddin II diduga membantai utusan Inggris. Pasukan Inggris menggulingkan sultan tersebut dan memasang penguasa yang ramah, sambil juga menduduki Pulau Bangka di lepas pantai Sumatra. Bangka (dengan tambang timahnya yang berharga) dimaksudkan sebagai basis cadangan Inggris jika Jawa harus diserahkan nanti.
Selama tahun-tahun ini, Inggris juga mempertahankan kendali atas pulau-pulau Maluku (yang direbut pada tahun 1810) dan wilayah Belanda yang lebih kecil. Mereka merekrut orang Ambon dan penduduk lokal lainnya ke dalam pasukan bantuan di bawah komando Inggris. Pemerintahan Inggris dengan demikian didirikan, meskipun singkat, di wilayah yang luas: Jawa, bagian Sumatra, pulau-pulau rempah-rempah Maluku, dan pulau-pulau timur lainnya.
Di bawah administrasi Inggris, pekerjaan budaya dan ilmiah yang penting juga berlangsung. Raffles memiliki minat mendalam dalam sejarah dan budaya Jawa. Pada tahun 1814, ia mensponsori penggalian Borobudur, candi Buddha monumental abad ke-9 yang terkubur di bawah hutan di Jawa Tengah. Perwira dan sarjana Inggris, seperti Colin Mackenzie dan H.C. Cornelius, mensurvei dan membersihkan situs-situs seperti Borobudur dan Prambanan, mendokumentasikan monumen kuno Jawa untuk pertama kalinya.
Raffles sendiri mengumpulkan manuskrip Jawa, barang antik, dan spesimen alam. Upaya ini mengarah pada publikasi karya monumentalnya History of Java pada tahun 1817, yang memperkenalkan peradaban Jawa kepada khalayak Eropa. Dengan demikian, bahkan di tengah konflik, periode Inggris melihat berkembangnya penelitian dan pertukaran budaya.
Penyerahan Kembali kepada Belanda (1816) dan Dampak Selanjutnya
Pemerintahan Inggris di Jawa selalu dimaksudkan untuk sementara, didorong oleh keadaan darurat Perang Napoleon. Di Eropa, perang berakhir dengan kekalahan Napoleon pada tahun 1814, dan Inggris setuju untuk mengembalikan sebagian besar koloni Belanda. Perjanjian Anglo-Belanda tahun 1814 (sering disebut Konvensi London 1814) menetapkan bahwa Jawa dan wilayah Hindia Timur Belanda lainnya dikembalikan ke Belanda.
Administrasi Raffles kemudian bersiap untuk menyerahkan kekuasaan. Pada Maret 1816, Sir Stamford Raffles dicopot dari jabatannya (sebagian karena perselisihan tentang keuangan koloni) dan digantikan oleh John Fendall Jr., yang menjabat sebagai gubernur sementara. Pada Agustus 1816, Komisaris Belanda (dipimpin oleh Gubernur Jenderal van der Capellen) tiba di Batavia, dan Inggris secara resmi menyerahkan Jawa kembali ke pemerintahan Belanda.
Pasukan Inggris menarik diri, mengakhiri lima tahun pemerintahan. Banyak reformasi Raffles akan segera dibatalkan di bawah administrasi Belanda yang kembali. Bahkan setelah 1816, Inggris mempertahankan pijakan di Sumatra selama beberapa tahun lagi. Koloni Bencoolen (Bengkulu) di pantai barat Sumatra tetap menjadi milik Inggris hingga 1824, melanjutkan perdagangan ladanya di bawah Raffles (yang ditempatkan di sana sebagai letnan gubernur dari tahun 1818).
Raffles terkenal menggambarkan Bencoolen sebagai "tempat paling menyedihkan yang pernah saya lihat," tetapi ia memberlakukan langkah-langkah progresif di sana, seperti menghapuskan perbudakan di wilayah itu. Pada akhirnya, Perjanjian Anglo-Belanda tahun 1824 secara permanen menyelesaikan pembagian Asia Tenggara antara kedua kekuatan.
Dalam perjanjian itu, Inggris menyerahkan Bencoolen dan semua klaim Inggris di Sumatra kepada Belanda, sebagai ganti India Belanda dan wilayah Semenanjung Melayu (terutama akuisisi Inggris atas Malaka). Perjanjian ini menggambar batas-batas wilayah kolonial Inggris dan Belanda yang pada akhirnya akan membentuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura modern.
Setelah tahun 1824, Inggris tidak lagi memegang wilayah apa pun di Indonesia, sebaliknya fokus pada Semenanjung Melayu (Singapura, Malaya) dan utara Borneo. Perlu dicatat bahwa ada interlude militer Inggris kemudian di Indonesia setelah Perang Dunia II (1945), ketika pasukan Sekutu yang dipimpin Inggris mendarat untuk melucuti pasukan Jepang dan sempat bertempur melawan nasionalis Indonesia dalam pertempuran seperti di Surabaya. Namun, itu adalah episode pascaperang yang singkat, bukan administrasi kolonial, dan berbeda dari pemerintahan Inggris awal abad ke-19 yang dibahas di sini.
Pemerintahan dan Struktur Politik di Bawah Kekuasaan Inggris
Administrasi dan Kebijakan Inggris
Selama interregnum Inggris (1811-1816), Sir Stamford Raffles berusaha membentuk kembali pemerintahan kolonial Jawa sesuai dengan garis yang lebih "tercerahkan". Ia mewarisi kerangka kerja dari Gubernur Jenderal Belanda sebelumnya Herman Willem Daendels (yang telah mereorganisasi Jawa menjadi distrik atau residensi di bawah pemerintahan Prancis-Belanda, 1808-1811).
Raffles melanjutkan dan memperluas reformasi administratif ini. Jawa dibagi menjadi sekitar 16 Residensi, masing-masing dipimpin oleh Residen Eropa yang bertanggung jawab atas administrasi lokal, keadilan, dan pertanian, dan melapor kepada pemerintah pusat di Batavia. Raffles mempertahankan banyak pegawai negeri Belanda yang berpengalaman untuk menjaga agar birokrasi tetap berjalan, tetapi dia menempatkan mereka di bawah pengawasan Inggris dan memperkenalkan pejabat Inggris ke posisi senior. Ini memastikan kesinambungan dalam pemerintahan lokal sambil menerapkan kebijakan baru.
Salah satu ciri khas pemerintahan Inggris adalah upaya untuk memperkenalkan unsur pemerintahan mandiri lokal dan mengurangi aturan sewenang-wenang. Raffles mengizinkan pejabat pribumi (seperti bupati atau bupati) peran berkelanjutan dalam administrasi, dan bahkan menyarankan pembentukan dewan penasihat lokal, sebuah pendekatan yang digambarkan sebagai "pemerintahan mandiri parsial".
Para bangsawan Jawa tradisional dipertahankan sebagai lapisan perantara administrasi (sistem pemerintahan ganda), tetapi tugas mereka didefinisikan ulang. Di bawah VOC Belanda, kepala suku lokal sering bertindak sebagai penguasa semi-feodal yang mengekstraksi kerja paksa dan upeti. Raffles membatasi praktik-praktik ini dan sebaliknya membuat banyak bupati menjadi administrator bergaji yang bertanggung jawab kepada pemerintah kolonial.
Ini adalah pergeseran politik yang signifikan: otoritas elit pribumi sekarang secara resmi mengalir dari administrasi kolonial yang dimaksudkan untuk bertindak demi kepentingan "publik" (seperti yang dilihat Inggris), bukan dari hak turun-temurun untuk mengeksploitasi petani. Raffles percaya sistem ini akan lebih adil dan efisien, sambil tetap memanfaatkan struktur kekuasaan yang ada untuk memerintah populasi.
Dalam hal struktur hukum dan peradilan, Inggris memperkenalkan reformasi untuk membuat pemerintahan kolonial lebih teratur dan terikat hukum. Raffles mereorganisasi sistem pengadilan dan kepolisian di Jawa. Pengadilan Tinggi didirikan di Batavia (dipimpin oleh sisa Belanda, Herman Warner Muntinghe) untuk berfungsi sebagai puncak keadilan. Otoritas Inggris bertujuan memastikan peradilan yang lebih tidak memihak dan melembagakan supremasi hukum menggantikan arahan VOC ad-hoc.
Kepolisian juga direformasi untuk lebih menjaga ketertiban umum. Misalnya, Raffles mengakhiri beberapa hukuman sewenang-wenang dan korupsi yang telah umum terjadi. Dia juga menyelaraskan kebijakan tertentu dengan norma-norma kekaisaran Inggris yang lebih luas, seperti bergerak untuk menekan perdagangan budak.
Di Jawa, Raffles mengeluarkan pembatasan pada pembelian dan penjualan budak (konsisten dengan penghapusan Inggris atas perdagangan budak pada tahun 1807). Meskipun perbudakan itu sendiri tidak sepenuhnya dihapuskan di Jawa dan budak masih ditemukan bahkan di rumah tangga Raffles, langkah-langkah ini menandakan pergeseran menuju pemerintahan yang lebih manusiawi.
Singkatnya, Inggris berusaha memperkenalkan administrasi birokrasi yang lebih bersih, dengan undang-undang dan peraturan yang dikodifikasi, layanan sipil bergaji, dan beberapa pertimbangan untuk masukan lokal, sebuah perubahan penting dari rezim VOC yang lebih merkantil dan koersif.
Sistem Pajak Tanah dan Pendapatan
Mungkin perubahan kebijakan paling mendalam di bawah pemerintahan Inggris adalah perombakan sistem agraria dan perpajakan. Raffles bertekad untuk mengganti sistem pengiriman paksa dan iuran feodal Belanda dengan sistem berbasis pendapatan modern. Pada tahun 1811, ia menghapuskan kontingen VOC dan sistem kerja paksa, yang telah mengharuskan desa-desa untuk mengirimkan kuota tetap tanaman (seperti beras, kopi, rempah-rempah) kepada pemerintah dengan harga rendah.
Sebagai gantinya, dia memperkenalkan sistem sewa tanah (pajak tanah) yang dimodelkan sebagian pada praktik pendapatan India Britania. Di bawah sistem ini, petani Jawa menjadi pembayar pajak, berhutang sebagian dari nilai panen mereka sebagai sewa tanah kepada negara kolonial daripada bekerja untuk atasan feodal mereka. Pajak ditetapkan sekitar 40% (dua perlima) dari hasil panen tahunan.
Secara teori, setiap surplus di luar pajak dapat disimpan atau dijual oleh petani dengan bebas. Kebijakan ini, sering disebut landrente atau "sistem pajak tanah," pada dasarnya adalah bentuk sewa tetap yang dibayarkan dalam bentuk tunai atau barang, mengubah petani dari buruh paksa menjadi pemilik tanah kecil (meskipun dikenai pajak).
Reformasi kepemilikan tanah Raffles dipengaruhi oleh ide-ide liberal sebelumnya dari dunia Belanda. Dia mengambil dari tulisan-tulisan Dirk van Hogendorp, seorang pejabat Belanda yang telah mengkritik kendala feodal di Jawa, mengadvokasi tenaga kerja dan perusahaan bebas. Raffles berkonsultasi dengan konsep Hogendorp dan dinasihati oleh H.W. Muntinghe (ahli hukum Belanda yang mengepalai Pengadilan Tinggi Jawa) tentang bagaimana menerapkan pajak tanah secara pragmatis.
Muntinghe memperingatkan tentang perlawanan dari bupati Jawa, yang akan kehilangan pendapatan tradisional mereka. Raffles melanjutkan dengan hati-hati, secara bertahap melembagakan pajak tanah di wilayah-wilayah di mana itu paling dapat dikerjakan. Efek langsungnya adalah membongkar sistem tributary lama: petani tidak lagi terikat untuk menyediakan tenaga kerja atau tanaman yang tidak dibayar kepada bangsawan lokal atau gudang kolonial; sebaliknya, mereka membayar pajak kepada pemerintah.
Bupati lokal dikompensasi dengan sebagian dari pendapatan pajak atau gaji untuk kerja sama mereka. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dengan memberi petani lebih banyak kebebasan untuk memilih tanaman mereka dan untuk merangsang ekonomi pasar di Jawa.
Perbandingan dengan Pemerintahan Belanda (Sebelum dan Sesudah)
Pemerintahan Inggris di Indonesia sangat berbeda dalam nada dari era VOC sebelumnya dan negara kolonial Belanda berikutnya, meskipun hanya berlangsung waktu singkat. Di bawah VOC (1600-an hingga 1700-an), pemerintahan telah didorong secara komersial dan menindas, ditandai dengan monopoli, pengiriman paksa tanaman, dan aliansi dengan aristokrasi feodal.
Administrasi Raffles mencoba memecah pola ini. Dia menganut prinsip-prinsip liberal ekonomi dan pemerintahan: perdagangan bebas, perusahaan swasta, dan gagasan bahwa mengurangi penindasan akan merangsang kemakmuran. Misalnya, Jawa Inggris melihat berkembangnya pasar yang lebih bebas: pembatasan perdagangan internal dilonggarkan dan petani dapat menjual produk setelah kewajiban pajak dipenuhi.
Raffles membayangkan Jawa "ditinggikan...ke tingkat kebebasan dan kemakmuran" di bawah reformasi ini. Memang, laporan awal menunjukkan para petani menyambut baik pembebasan dari tuntutan Belanda yang memberatkan, dan beberapa pejabat Inggris mengklaim bahwa pertanian dan perdagangan Jawa merespons secara positif di daerah-daerah di mana pajak tanah diterapkan.
Namun, perubahan ini berumur pendek dan tidak diterapkan secara seragam. Ketika Belanda kembali pada tahun 1816, mereka menghadapi pilihan sulit: melanjutkan sistem Raffles atau kembali ke metode lama yang menjamin pendapatan lebih tinggi. Awalnya, administrasi Belanda yang dipulihkan mempertahankan beberapa inovasi Inggris. Mereka meninggalkan struktur residensi di tempat (terbukti efisien) dan bahkan bereksperimen dengan mempertahankan pajak tanah.
Tetapi dalam beberapa tahun, mereka menjadi tidak puas dengan hasil pendapatan dan tantangan mengumpulkan pajak tunai dari masyarakat petani. Akhirnya, pada tahun 1830 Belanda menghapuskan pendekatan pajak tanah di sebagian besar Jawa dan memperkenalkan Sistem Kultuur yang terkenal kejam (Cultuurstelsel) di bawah Gubernur Jenderal Van den Bosch.
Sistem ini memberlakukan kembali budidaya wajib tanaman ekspor (nila, kopi, gula, dll.) dan pengiriman paksa, pada dasarnya kembali ke eksploitasi gaya VOC, meskipun sekarang di bawah kendali negara langsung. Reformasi liberal Raffles dengan demikian "dihapus secara bertahap" setelah 1816, dengan Belanda kembali ke kerja paksa, kuota tanaman, dan monopoli.
Dalam hal struktur politik, negara kolonial Belanda (setelah 1816) terus menggunakan hierarki ganda yang telah dibentuk Raffles dan Daendels: layanan sipil Eropa yang memerintah bersama (dan di atas) aristokrasi pribumi. Namun, Belanda cenderung memperketat kendali atas pejabat pribumi dan menuntut kepatuhan mutlak pada mandat kolonial.
Selama abad ke-19, jumlah pejabat Eropa di residensi membengkak, mencerminkan intervensi yang semakin dalam dalam masyarakat lokal. Sebaliknya, masa Raffles memiliki relatif sedikit orang Eropa di Jawa, memaksa sentuhan yang lebih ringan. Patut dicatat bahwa beberapa pejabat Belanda kemudian mengakui kontribusi Raffles, misalnya, Belanda melanjutkan studi ilmiah budaya Jawa yang dimulai Raffles dan mempertahankan Kebun Raya Bogor yang telah ia perluas di Buitenzorg.
Tetapi secara politik dan ekonomis, interlude Inggris adalah outlier, diingat oleh beberapa sejarah Indonesia sebagai periode pemerintahan yang lebih baik hati berbeda dengan kolonisasi Belanda. Raffles kemudian diidealkan oleh penulis nasionalis Indonesia tertentu sebagai seseorang yang meringankan beban rakyat (meskipun tujuan utamanya adalah pemerintahan yang efisien).
Kenyataannya adalah bahwa reformasi Inggris dibatasi oleh perang dan keuangan, dan setelah Jawa kembali di bawah otoritas Belanda, kekhawatiran keuntungan pragmatis menegaskan diri mereka atas kebijakan kemanusiaan.
Singkatnya, pemerintahan Inggris memperkenalkan kebijakan kolonial yang lebih liberal dan reformis, menekankan hukum, administrasi rasional, pengurangan penindasan feodal, dan keterlibatan dengan budaya lokal. Perubahan ini, bagaimanapun, sebagian besar dibalik ketika Belanda mendapatkan kembali kendali. Era Inggris berdiri sebagai eksperimen singkat dalam pemerintahan kolonial yang tercerahkan, "kesempatan yang hilang," seperti yang disarankan beberapa sejarawan, untuk secara permanen meningkatkan sistem kolonial.
Kebijakan Ekonomi dan Dinamika Perdagangan
Perdagangan dan Komoditas di Bawah Kekuasaan Inggris
Pertimbangan ekonomi berada di jantung kehadiran Inggris di Indonesia, seperti halnya dengan perusahaan kolonial mana pun. Interregnum Inggris melihat baik kesinambungan maupun perubahan dalam komoditas yang diperdagangkan dan kebijakan perdagangan yang diterapkan. Jawa dan pulau-pulau sekitarnya kaya akan tanaman ekspor dan sumber daya yang telah lama menjadi pusat perdagangan VOC: rempah-rempah (pala, cengkeh, bunga pala), kopi, teh (meskipun budidaya teh di Jawa dimulai kemudian), nila, gula, lada, dan lainnya.
Inggris secara aktif terlibat dalam perdagangan ini selama administrasi mereka. Salah satu tujuan langsung Inggris pada tahun 1811 adalah merebut Kepulauan Rempah (Maluku) untuk mengambil alih perdagangan rempah-rempah yang berharga. Dengan menaklukkan Ambon, Banda, dan Ternate, Inggris mendapatkan kendali langsung atas produksi pala dan cengkeh. EIC kemudian dapat mengekspor rempah-rempah ini melalui jaringannya sendiri, memecahkan monopoli Belanda yang panjang.
Di Sumatra, Bencoolen yang dikuasai Inggris berspesialisasi dalam lada. Inggris terus mengekspor lada Sumatra ke Eropa dan India. Di Jawa, Inggris mewarisi perkebunan kopi VOC di Priangan (Jawa Barat), dan perkebunan yang menghasilkan gula dan nila di dataran rendah. Raffles awalnya mengizinkan produksi ini berlanjut tetapi di bawah sistem sewa tanah baru (yang berarti petani akan membayar pajak atas output daripada mengirimkan kuota).
Pejabat Inggris juga mendorong budidaya tanaman pangan seperti beras untuk memastikan keamanan pangan, karena Jawa telah menderita kelaparan di bawah kebijakan sebelumnya.
Liberalisasi Perdagangan
Pergeseran signifikan di bawah pemerintahan Inggris adalah bergerak menuju kebijakan perdagangan bebas. VOC Belanda telah beroperasi pada model tertutup, monopolistik: produk tertentu hanya dapat dijual kepada Perusahaan, dan semua perdagangan asing dengan Nusantara dikendalikan ketat di Batavia.
Raffles, dipengaruhi oleh pemikiran ekonomi liberal Inggris, bertujuan untuk "memperluas perdagangan" dan mengakhiri praktik restriktif. Di Jawa, administrasi Inggris membuka pelabuhan untuk lebih banyak pedagang, termasuk pedagang Amerika, Cina, India, dan Inggris dari Kalkuta. Mereka mengurangi bea ekspor dan pajak transit internal yang telah menghambat perdagangan.
Raffles menghapuskan sistem pas VOC yang dibenci yang mengharuskan pedagang pribumi untuk mendapatkan pas untuk memindahkan barang, dengan demikian merangsang pasar internal. Meskipun perang dan transisi berarti kekacauan ekonomi awalnya, langkah-langkah ini berusaha mengintegrasikan ekonomi Jawa dengan jaringan perdagangan Inggris yang lebih luas di Asia.
Salah satu tindakan Inggris yang paling konsekuensial adalah redistribusi global tanaman berharga dari Indonesia. Setelah merebut pulau-pulau penghasil rempah-rempah, Inggris tidak membuang waktu dalam mentransfer tanaman-tanaman itu ke tempat lain. Pada tahun 1810-1811, ahli botani dan perwira Inggris mengambil bibit pala dari Banda dan bibit cengkeh dari Ambon, mengirimnya ke koloni Inggris seperti Ceylon (Sri Lanka) dan Penang.
Pada tahun 1817, pohon pala berkembang di Ceylon dan juga di pulau Grenada di Karibia, yang dikontrol Inggris. Demikian juga, budidaya cengkeh menyebar ke wilayah Inggris. Ini memecahkan monopoli Belanda atas rempah-rempah, sebuah monopoli yang telah berlangsung hampir dua abad. Akibatnya, harga global cengkeh dan pala akhirnya turun, dan kepentingan strategis pulau-pulau Maluku berkurang dari waktu ke waktu.
Akibatnya, kebijakan ekonomi Inggris selama pendudukan mempercepat integrasi komoditas Indonesia ke dalam sistem perdagangan global yang lebih luas yang tidak dikendalikan hanya oleh Belanda. Produk Jawa (kopi, gula, nila) mulai diperdagangkan melalui Kalkuta dan London, dan rempah-rempah memasuki pasar dunia melalui berbagai saluran.
Kepemilikan Tanah dan Dampak Ekonominya
Pengenalan pajak tanah (landrente) bukan hanya reformasi politik tetapi juga reformasi ekonomi. Di bawah sistem ini, petani secara teoritis memiliki kebebasan yang lebih besar: setelah membayar pajak mereka (sekitar 40% dari hasil), mereka dapat mengonsumsi atau menjual tanaman mereka sesuka mereka. Ini diharapkan akan memberikan insentif produksi karena petani dapat mengambil untung dari surplus.
Raffles percaya bahwa ketika dibebaskan dari pengiriman paksa, petani Jawa akan mengolah lebih banyak tanah dan lebih banyak tanaman yang beragam, merespons permintaan pasar dan menguntungkan ekonomi. Untuk memfasilitasi ini, administrasi Inggris mengizinkan pedagang swasta (termasuk pedagang lokal dan asing) untuk membeli produk dari penduduk desa, sedangkan sebelumnya monopoli VOC akan menetapkan harga.
Ada bukti bahwa di beberapa wilayah, beras dan bahan pokok lainnya menjadi lebih tersedia di pasar, dan petani wirausaha meningkatkan penanaman tanaman tunai seperti lada atau kopi atas inisiatif mereka sendiri. Inggris juga mencoba memperkenalkan bentuk ekonomi tunai di pedesaan Jawa: mereka membayar pejabat dan bahkan beberapa petani dalam rupee perak (dibawa dari India) untuk mengedarkan mata uang, berharap ini akan membantu petani membayar pajak tanah dan berpartisipasi dalam perdagangan.
Terlepas dari niat ini, hasil ekonomi dari kebijakan Raffles beragam. Dalam jangka pendek, pendapatan koloni anjlok. Pajak tanah terbukti sulit untuk dinilai dan dikumpulkan: banyak petani terbiasa membayar dalam bentuk barang atau melakukan kerja paksa, dan perubahan mendadak ke penilaian tunai menyebabkan kebingungan dan penghindaran.
Administrasi Inggris tidak memiliki staf terlatih yang memadai dan data survei untuk menerapkan sistem dengan benar di semua area. Beberapa elit lokal menolak atau secara diam-diam mensubversi pajak baru, dan produksi barang ekspor tertentu (seperti budidaya kopi paksa di Priangan) menurun ketika paksaan dihilangkan.
Pada tahun 1815, EIC menghadapi defisit keuangan di Jawa, karena sewa tanah membawa jauh lebih sedikit uang daripada metode VOC lama. Idealisme Raffles berbenturan dengan permintaan Perusahaan Hindia Timur untuk keuntungan: reformasinya dianggap terlalu mahal dan tidak segera menguntungkan. Ini adalah alasan utama ia tidak disukai oleh Perusahaan.
Dengan demikian, sementara kebijakan Inggris mungkin telah menguntungkan penduduk Jawa dalam meringankan beban, mereka membebani anggaran koloni. Namun demikian, pemerintahan ekonomi Inggris memang meninggalkan beberapa dampak yang bertahan lama. Filosofi perdagangan bebas mereka kemudian akan mempengaruhi Belanda: setelah tahun 1870, Hindia Belanda beralih ke ekonomi pasar bebas (akhir Sistem Kultuur dan awal modal perkebunan swasta), agak menggemakan sikap Raffles sebelumnya.
Perjanjian Anglo-Belanda tahun 1824, dengan mengukir wilayah, menempatkan Nusantara Indonesia dengan kuat di bawah pengaruh ekonomi Belanda sementara Inggris mengambil Malaya. Ini memiliki konsekuensi jangka panjang: itu memastikan bahwa perdagangan Indonesia akan diorientasikan ke pasar Belanda (dan kemudian global), sedangkan Semenanjung Melayu (dengan Singapura) menjadi pusat perdagangan bebas di bawah Inggris.
Bahkan, pendirian Singapura oleh Raffles pada tahun 1819, meskipun di luar lingkup Indonesia, memiliki efek tidak langsung yang mendalam pada ekonomi Indonesia. Kebangkitan Singapura sebagai pelabuhan bebas menarik banyak perdagangan yang pernah melalui pelabuhan yang dikendalikan Belanda seperti Batavia, Palembang, atau Riau. Produsen Indonesia menemukan outlet alternatif untuk menyelundupkan atau menjual barang melalui Singapura Inggris, menekan Belanda untuk akhirnya meliberalisasi perdagangan.
Singkatnya, Inggris memperkenalkan kebijakan ekonomi ramah pasar di Indonesia: menghilangkan monopoli, mendorong perdagangan terbuka, dan melembagakan sistem pajak yang dimaksudkan untuk merangsang produktivitas. Mereka secara agresif memanfaatkan kendali singkat mereka untuk memperoleh dan menyebarkan komoditas berharga Indonesia (rempah-rempah) di seluruh Kekaisaran Inggris, mengintegrasikan Nusantara ke dalam jaringan perdagangan global yang lebih luas di luar kendali Belanda.
Sementara keuntungan ekonomi jangka pendek untuk Inggris terbatas, dan eksperimen berakhir dengan kekecewaan finansial bagi Perusahaan Hindia Timur, kebijakan ini memiliki efek jangka panjang yang signifikan pada dinamika perdagangan global dan meramalkan perubahan ekonomi yang akan datang kemudian di abad ke-19.
Konflik Militer dan Gerakan Perlawanan
Kampanye Militer Inggris (1811-1816)
Kendali Inggris di Indonesia didirikan dan dipertahankan melalui beberapa aksi militer. Invasi awal Jawa pada tahun 1811 adalah kampanye yang direncanakan dan dieksekusi dengan baik selama Perang Napoleon. Dipimpin oleh Kolonel Rollo Gillespie di bawah pengawasan Gubernur Jenderal Lord Minto, pasukan Inggris-India (sekitar 10.000 orang, sebagian besar sepoy India) mendarat dan bertempur dalam kampanye cepat melawan pasukan Franco-Belanda.
Pertempuran kunci termasuk penangkapan Batavia (Jakarta) pada 8 Agustus 1811 dan penyerbuan benteng Meester Cornelis pada 26 Agustus 1811, yang secara efektif memecahkan perlawanan Belanda di Jawa. Gubernur Belanda Janssens menyerah segera setelahnya, melarikan diri dan akhirnya menyerah pada bulan September.
Kemenangan menentukan ini dicapai dengan korban Inggris yang relatif terbatas, sementara pasukan pertahanan Belanda-Prancis menderita kerugian sangat berat. Kesuksesan itu sebagian disebabkan oleh kekuatan angkatan laut Inggris yang superior dan penggunaan pasukan India yang berpengalaman dan perwira Inggris yang telah bertempur dalam ekspedisi kolonial serupa.
Setelah mengamankan Jawa, Inggris harus mengkonsolidasikan kendali. Mereka menghadapi kantong perlawanan dari beberapa pasukan lokal yang setia kepada administrasi Belanda lama atau hanya menolak dominasi asing apa pun. Konflik paling terkenal adalah dengan Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1812.
Sultan Hamengkubuwono II, yang marah dengan reformasi Belanda sebelumnya di bawah Daendels dan pemerintahan Inggris yang baru, diyakini merencanakan pemberontakan. Raffles memutuskan untuk menetralisir ancaman ini secara preemptif. Pada Juni 1812, ia memimpin pasukan tentara Inggris, sepoy, dan pembantu Madura untuk menyerang Yogyakarta.
Inggris menyerbu kraton (istana) dan merebutnya dalam satu hari (20 Juni 1812). Mereka menggulingkan Sultan, memasang putranya di atas takhta di bawah pengawasan Inggris, dan mengambil rampasan perang. Tunjangan kekuatan ini membuat istana-istana Jawa lainnya takut. Sunanate Surakarta, misalnya, tetap patuh dan bersekutu dengan Inggris (seperti halnya dengan Belanda).
Kemudahan kemenangan Inggris di Yogyakarta mengejutkan Jawa. Ini adalah pertama kalinya kekuatan pribumi utama telah disubordinasikan secara langsung dan keras oleh orang Eropa. Inggris dengan demikian mengirim pesan yang jelas bahwa pemberontakan akan dihancurkan.
Aksi militer lainnya adalah ekspedisi melawan Palembang (Sumatra) pada tahun 1812. Sultan Mahmud Badaruddin II dari Palembang memiliki sejarah gesekan dengan Belanda dan, ketika kekuatan Belanda melemah pada tahun 1811, ia diduga membantai kontingen Belanda. Raffles mengirim pasukan dengan kapal ke Palembang: Sultan digulingkan dan digantikan dengan saudaranya yang lebih kooperatif.
Inggris juga mengambil kendali Pulau Bangka, yang termasuk Kesultanan Palembang, mengamankan tambang timahnya yang berharga. Operasi ini memperluas kehadiran militer Inggris ke Sumatra, meskipun wilayah itu periferal terhadap perhatian utama mereka (Jawa).
Lebih jauh, sepanjang tahun 1811-1816, pasukan Inggris harus memastikan Maluku tetap tenang. Inggris telah menduduki Ambon dan Banda pada tahun 1810 tanpa banyak perlawanan lokal (garnisun Belanda menyerah). Mereka mempertahankan garnisun di sana, terdiri sebagian dari sepoy dan rekrutan lokal seperti tentara Kristen Ambon. Ada bentrokan minimal selama masa jabatan Inggris di Maluku; memang, beberapa penduduk lokal bekerja sama dengan Inggris, tidak memiliki cinta untuk monopoli Belanda sebelumnya.
Perlawanan Indonesia dan Reaksi
Interregnum Inggris terlalu singkat untuk memicu gerakan perlawanan pribumi yang berbasis luas yang sebanding dengan perang anti-Belanda kemudian. Banyak penguasa lokal memilih untuk mengakomodasi atau bersekutu dengan Inggris, melihat mereka sebagai penguasa sementara atau lebih disukai. Khususnya, penguasa Surakarta dan beberapa pangeran di Jawa menerima kedaulatan Inggris dan bahkan membantu administrasi Raffles.
Namun, perlawanan memang terjadi dalam insiden terlokalisasi, terutama ketika kepentingan Inggris bertabrakan dengan otoritas pribumi. Di Yogyakarta (1812), sikap Sultan Hamengkubuwono II menyebabkan perang. Setelah kemenangan Inggris, ada kebencian yang bertahan di antara bangsawan Jawa.
Meskipun pertempuran terbuka berhenti, penghinaan Yogyakarta menabur benih ketidakpuasan. Catatan Inggris mencatat bahwa serangan itu "mungkin telah memicu...permusuhan terhadap keterlibatan Eropa" di Jawa tengah. Memang, beberapa sejarawan menghubungkan ini dengan keluhan mendalam yang kemudian meledak dalam Perang Jawa (1825-1830) melawan Belanda.
Inggris tidak hadir saat itu, tetapi gangguan mereka terhadap tatanan tradisional (mengulingkan sultan, dll.) berkontribusi secara tidak langsung pada perlawanan kemudian di bawah Pangeran Diponegoro. Di Palembang, deposisi sultan Inggris kemungkinan menghindari perjuangan anti-kolonial potensial pada saat itu. Tetapi Sultan Mahmud Badaruddin II yang digulingkan tetap menjadi tokoh perlawanan; ketika Belanda kembali, konflik di Palembang meletus lagi pada tahun 1819 dengan mantan sultan mencoba merebut kembali takhtanya.
Sikap masyarakat pribumi terhadap Inggris sering tergantung pada bagaimana mereka telah diperlakukan oleh Belanda. Di daerah-daerah di mana Belanda telah keras, beberapa penduduk lokal menyambut Inggris sebagai pembebas. Misalnya, orang Ambon dan lain-lain di Maluku awalnya menunjukkan sedikit perlawanan terhadap pendudukan Inggris.
Ketika Belanda kembali pada tahun 1817 dengan rencana untuk mengembalikan otoritas mereka dan mungkin merekrut penduduk lokal ke dalam tentara kolonial baru (KNIL), sebuah pemberontakan serius meletus. Seorang veteran yang pernah bertugas dengan Inggris, Thomas Matulessy, lebih dikenal sebagai Kapitan Pattimura, memimpin pemberontakan di Maluku pada Mei 1817.
Pattimura dan para pengikutnya takut penindasan yang lebih keras di bawah Belanda daripada yang mereka alami di bawah Inggris. Mereka merebut Benteng Duurstede di pulau Saparua dan membunuh residen Belanda, memproklamirkan akhir pemerintahan Belanda. Pemberontakan akhirnya ditekan oleh pasukan Belanda, dan Pattimura ditangkap dan dieksekusi pada akhir 1817.
Pemberontakan ini mengungkapkan: itu menunjukkan bahwa pemerintahan Inggris relatif lunak atau setidaknya dapat ditoleransi untuk orang Ambon, cukup bahwa kembalinya Belanda memicu perlawanan bersenjata segera. Perang Pattimura, meskipun setelah periode Inggris, menggarisbawahi perbedaan dalam persepsi lokal: pemerintahan Inggris tidak menginspirasi reaksi keras seperti itu, sedangkan upaya untuk mengembalikan kendali Belanda terjadi.
Secara keseluruhan, perlawanan Indonesia selama periode Inggris terbatas dan sebagian besar dipimpin oleh elit (seperti yang terlihat dengan istana Yogyakarta dan Sultan Palembang). Tidak ada gerakan nasionalis massa: gagasan tentang nasionalisme Indonesia belum ada pada tahun 1811, dan sebagian besar petani mungkin merasakan sedikit perbedaan apakah mereka menjawab kepada pejabat Belanda atau Inggris, selama pajak dan tuntutan tenaga kerja dapat ditanggung.
Bahkan, beberapa rakyat jelata mungkin merasakan sedikit kelegaan di bawah kebijakan Inggris (karena pelonggaran beban), yang dapat mengurangi dorongan untuk pemberontakan. Namun, setiap kali kebijakan Inggris mengancam struktur kekuasaan atau tradisi pribumi, konflik dapat memicu. Contoh terbaik adalah Yogyakarta, di mana campur tangan Inggris dengan suksesi kerajaan dan penjarahan mereka terhadap kraton sangat menyinggung sensibilitas Jawa, bahkan jika itu tidak menghasilkan perlawanan gerilya langsung.
Administrasi Militer Dibandingkan dengan Belanda dan Jepang
Pendekatan Inggris terhadap kontrol militer dan pasifikasi di Indonesia memiliki beberapa fitur unik ketika dikontraskan dengan rezim kolonial Belanda sebelum dan sesudahnya, dan pendudukan Jepang kemudian. Inggris sangat bergantung pada pasukan dari tempat lain di kekaisaran mereka, sepoy India misalnya, untuk menaklukkan dan mengawasi Jawa.
Ini memberi mereka pasukan disiplin yang tidak terhubung secara lokal, mengurangi kemungkinan simpati atau kolusi dengan populasi lokal. Belanda, sebaliknya, secara bertahap membangun KNIL (Tentara Hindia Belanda Kerajaan) yang merekrut banyak tentara pribumi (terutama dari Ambon, Minahasa, Jawa, dll.) pada pertengahan dan akhir abad ke-19.
Selama era VOC, Belanda juga menggunakan tentara bayaran dari berbagai kelompok etnis. Administrasi lima tahun Inggris terlalu singkat untuk mendirikan militer lokal, meskipun mereka mempersenjatai beberapa milisi lokal (seperti di Ambon). Jepang (1942-45) awalnya hanya menggunakan pasukan Jepang untuk menduduki Indonesia, tetapi kemudian membentuk pasukan bantuan lokal (PETA) menjelang akhir perang. Jepang brutal dalam mempertahankan kendali, sedangkan Inggris umumnya menerapkan kekuatan lebih selektif.
Kampanye militer kolonial Belanda di Indonesia, terutama pada abad ke-19, sangat banyak dan sering berlarut-larut, misalnya, Perang Jawa (1825-30), Perang Padri di Sumatra (1820-an), Perang Banjarmasin (1859-63), dan Perang Aceh yang panjang dan berdarah (1873-1904). Konflik ini melibatkan taktik bumi hangus dan korban lokal besar selama bertahun-tahun.
Periode Inggris tidak melihat apa pun pada skala itu, terutama karena durasi singkat dan fakta bahwa Inggris menyerahkan koloni alih-alih menaklukkannya dalam jangka panjang. Pemerintahan Inggris, selain serangan dramatis di Yogyakarta, tidak memerlukan kampanye militer yang meluas terhadap penduduk.
Raffles sebenarnya bangga memenangkan banyak pangeran Jawa dengan diplomasi, misalnya, ia mengelola hubungan dengan Susuhunan Surakarta secara damai dan menghormati perjanjian yang ada. Sebagai perbandingan, pendudukan Jepang sangat keras: mereka memberlakukan darurat militer, menciptakan negara polisi, dan memenuhi perlawanan apa pun dengan eksekusi dan teror.
Pemberontakan lokal di bawah pemerintahan Jepang (seperti pemberontakan anti-Jepang di Jawa Barat pada tahun 1943, atau pemberontakan Blitar oleh PETA pada tahun 1945) dipenuhi dengan penindasan cepat dan brutal. Inggris pada tahun 1811-16 tentu menggunakan kekuatan militer ketika diperlukan (seperti yang terlihat di Yogyakarta), tetapi mereka tidak menggunakan teror sistematis terhadap warga sipil atau mobilisasi paksa yang luas orang Indonesia ke dalam tentara mereka.
Inggris sebagian besar memerintah melalui struktur pribumi yang ada, yang mengurangi kebutuhan akan penegakan militer konstan. Setelah penaklukan awal, mereka tidak mempertahankan pasukan pendudukan besar di setiap desa; sebaliknya, mereka memanfaatkan penguasa lokal. Belanda juga sering memerintah secara tidak langsung (sistem "pemerintahan ganda"), tetapi ketika penguasa lokal menolak, Belanda akan menggulingkan atau menghukum mereka, dan pada akhir abad ke-19, Belanda bergerak menuju pemerintahan yang lebih langsung, yang menyebabkan lebih banyak ekspedisi militer untuk mengintegrasikan wilayah independen (seperti Aceh, Bali, Lombok).
Jepang awalnya membongkar banyak birokrasi pribumi yang diciptakan Belanda dan memerintah langsung melalui militer, yang menyebabkan kekacauan administratif dan kebencian. Pendekatan Inggris pada tahun 1811-16 relatif bersifat konsiliasi terhadap pangeran kooperatif (mereka memberi penghargaan kepada mereka yang membantu, seperti Sultan Yogyakarta baru yang mereka pasang, atau Bupati yang patuh dengan pengumpulan pajak).
Seseorang mungkin mengatakan Inggris menggabungkan tunjangan kekuatan yang kuat dengan pragmatisme berikutnya dan bahkan sanjungan terhadap elit pribumi, misalnya, Raffles memulihkan kehormatan istana tertentu dan mengizinkan bangsawan Jawa untuk menjaga gelar dan tanah mereka di bawah sistem baru, berharap untuk melegitimasi pemerintahan Inggris.
Dalam membandingkan rezim ini, kita melihat bahwa interregnum Inggris secara militer singkat dan tajam: penaklukan cepat diikuti oleh penindasan pemberontakan elit yang ditargetkan. Belanda, dengan masa jabatan yang jauh lebih lama, harus melakukan operasi militer terus-menerus untuk memperluas dan mengamankan koloni mereka, menghadapi beberapa generasi perlawanan.
Pemerintahan Jepang, meskipun hanya 3½ tahun, adalah selama masa perang dan ditandai dengan eksploitasi keras (kerja paksa, eksekusi) jauh lebih buruk daripada apa pun di periode kolonial Inggris atau Belanda. Orang Indonesia yang hidup melalui Perang Dunia II sering menganggap kembalinya Inggris singkat pada akhir 1945 sebagai pembebas dari Jepang, ironis berbeda dari bagaimana Inggris dilihat pada tahun 1811 ketika mereka adalah kekuatan kolonial asing lain yang menggantikan yang lain.
Perspektif tergantung pada konteks: pada tahun 1811, Inggris adalah satu kekuatan kolonial Eropa yang menggantikan yang lain; pada tahun 1945, pasukan Inggris mewakili pemenang Sekutu yang mengakhiri pendudukan Jepang yang brutal, meskipun tujuan mereka juga untuk mengembalikan pemerintahan Belanda yang menyebabkan bentrokan dengan republik Indonesia.
Singkatnya, keterlibatan militer Inggris di Indonesia ditandai dengan penaklukan yang efisien dan konflik yang relatif terbatas dengan penduduk lokal selama pendudukan. Di mana mereka bertempur (Yogyakarta, Palembang), itu untuk menghancurkan kekuatan penguasa yang mengancam otoritas mereka. Mereka tidak menghadapi atau tidak memprovokasi perlawanan populer yang meluas dalam pemerintahan singkat mereka.
Ini dapat dikontraskan dengan Belanda, yang terlibat dalam banyak perang panjang untuk menaklukkan Nusantara, dan Jepang, yang taktik opresifnya membiakkan kebencian dan pemberontakan yang mendalam. Pendekatan Inggris yang relatif moderat (terlepas dari episode keras tertentu) meninggalkan warisan yang kompleks: beberapa orang Indonesia kemudian mengingat periode Inggris sebagai kurang memberatkan daripada pemerintahan Belanda, namun itu terlalu singkat untuk memicu baik loyalitas yang bertahan lama atau perlawanan jangka panjang di antara penduduk.
Pertukaran Budaya dan Dampak Sosial
Dampak pada Struktur dan Hierarki Sosial
Interregnum Inggris membawa perubahan halus namun penting pada struktur sosial Indonesia, terutama di Jawa. Dengan membatasi kekuasaan aristokrasi lokal dalam hal ekonomi, administrasi Raffles secara tidak sengaja mulai mengubah hierarki tradisional. Di bawah sistem Belanda sebelumnya, bangsawan Jawa (bupati, wedana, dll.) mengekstraksi tenaga kerja dan tanaman dari petani, memperkuat tatanan sosial mirip-feodal.
Penghapusan kerja paksa dan pengenalan pajak tanah oleh Raffles berarti bahwa, pada prinsipnya, petani berurusan dengan negara kolonial lebih langsung daripada melalui tuan feodal mereka. Peran banyak bangsawan bergeser dari tuan ke administrator: mereka sekarang menjadi pejabat bergaji yang memediasi pengumpulan pajak dan pemerintahan.
Pengurangan otoritas eksploitatif mereka sedikit meratakan piramida sosial: penduduk desa biasa memiliki sedikit lebih banyak otonomi dalam pekerjaan mereka (karena mereka dapat memilih bagaimana memenuhi kewajiban pajak mereka daripada mematuhi tuntutan corvée sewenang-wenang). Tentu saja, struktur kolonial masih sangat hirarkis: pejabat Eropa berada di puncak, diikuti oleh aristokrasi pribumi sebagai perantara, dan massa di bawah.
Tetapi kebijakan Inggris mencoba menyelaraskan kepentingan elit pribumi dengan tujuan kolonial dengan membuat mereka birokrat bergaji. Beberapa aristokrat membenci kehilangan hak istimewa tradisional mereka, sementara yang lain beradaptasi dengan tatanan baru. Realignment sosial ini bersifat jangka pendek, karena Belanda memulihkan banyak praktik lama kemudian. Namun, itu menetapkan preseden bahwa pemerintahan kolonial dapat mendefinisikan ulang dinamika kekuasaan lokal daripada hanya menegakkan mereka.
Dalam hal kehidupan sosial sehari-hari, pemerintahan Inggris terlalu singkat untuk secara dramatis mengubah tatanan masyarakat Indonesia, yang tetap pedesaan, agraria, dan dipandu oleh adat istiadat lokal (adat). Namun, praktik-praktik opresif tertentu dilonggarkan. Misalnya, seperti disebutkan, perbudakan melihat langkah-langkah menuju penghapusan di wilayah Inggris.
Raffles mengambil sikap moral yang kuat terhadap perbudakan: di Bencoolen (Sumatra), ia secara resmi menghapuskan perbudakan pada tahun 1818 dengan dekrit, membebaskan orang-orang yang diperbudak di wilayah itu. Di Jawa, sementara ia tidak langsung membebaskan semua budak, ia melarang perdagangan budak dan impor budak baru. Kebijakan ini mendahului penghapusan perbudakan Belanda beberapa dekade (Belanda menghapuskan perbudakan secara bertahap pada pertengahan abad ke-19).
Dampak sosial langsung terbatas: perbudakan tidak begitu lazim di Jawa seperti di beberapa koloni lain, tetapi secara simbolis ia menetapkan sikap resmi yang kemudian akan mempengaruhi kebijakan Belanda.
Dampak sosial lain adalah pada ekonomi petani dan kehidupan desa. Dengan berakhirnya budidaya wajib, desa-desa di beberapa daerah memiliki lebih banyak kontrol atas kalender pertanian mereka. Petani dapat memprioritaskan menanam padi untuk konsumsi mereka sendiri dan pasar lokal, meningkatkan keamanan pangan.
Pengumpul pajak Inggris memang berinteraksi dengan kepala desa (lurah) untuk menilai sewa tanah, yang memperkenalkan interaksi administratif baru di tingkat desa. Beberapa petani mengalami beban kerja yang lebih ringan daripada di bawah tuntutan Belanda, yang dapat menyebabkan perbaikan kecil dalam kesejahteraan selama tahun-tahun itu. Misalnya, laporan Inggris mencatat bahwa orang Jawa di distrik-distrik di mana beban dikurangi menunjukkan tanda-tanda kepuasan dan industri.
Namun, laporan-laporan ini mungkin optimis: transisi juga menyebabkan ketidakpastian di beberapa desa yang tidak terbiasa dengan sistem baru.
Pertukaran Budaya dan Linguistik
Terlepas dari durasi singkat, periode Inggris ditandai dengan minat mendalam dalam budaya Indonesia oleh tokoh-tokoh seperti Raffles dan rekan-rekannya. Raffles adalah seorang Orientalis yang rajin dan memiliki antusiasme asli untuk budaya dan sejarah Jawa. Ia mempekerjakan penerjemah dan sarjana (termasuk intelektual Jawa) untuk membantunya mempelajari teks-teks kuno dan adat istiadat lokal.
Di bawah patronase Raffles, administrasi Inggris mengumpulkan dan melestarikan banyak manuskrip Jawa, termasuk kronik (babad) dan karya sastra, yang mungkin sebaliknya akan hilang. Ini dikirim ke perpustakaan di Inggris atau Kalkuta. Teks-teks tersebut kemudian menjadi sumber penting untuk memahami sejarah dan sastra Indonesia.
Raffles juga mendukung dokumentasi bahasa Jawa dan Melayu. Salah satu perwiranya, John Crawfurd (Residen Yogyakarta setelah 1812), menyusun catatan ekstensif tentang bahasa Melayu dan kemudian menerbitkan kamus Melayu-Inggris dan tata bahasa bahasa Melayu (pada tahun 1852, setelah kembalinya ke Inggris).
Crawfurd juga menulis History of the Indian Archipelago (1820) yang mencakup survei etnografi luas dari wilayah tersebut. Karya linguistik dan etnografi oleh sarjana Inggris ini adalah di antara studi sistematis pertama tentang bahasa dan masyarakat Indonesia oleh orang Barat.
Periode Inggris juga mendorong pertukaran antarbudaya di istana-istana. Misalnya, setelah Inggris memasang sultan baru di Yogyakarta, mereka mempertahankan hubungan diplomatik dengan istana. Perwira Inggris menghadiri upacara dan terlibat dengan aristokrat Jawa; pada gilirannya, bangsawan Jawa terpapar adat istiadat Inggris.
Ada catatan tentang pangeran Jawa belajar beberapa kata bahasa Inggris atau mengadopsi mode Inggris tertentu (seperti seragam militer yang disajikan sebagai hadiah). Sementara itu, Raffles dan istrinya Olivia mengadopsi elemen gaya Jawa dalam gaya hidup mereka di Istana Buitenzorg: mereka melindungi pengrajin batik dan musisi gamelan, dan Olivia Raffles dikenal berbicara dalam bahasa Melayu dengan wanita lokal.
Interaksi seperti itu, meskipun terbatas pada elit, adalah bentuk pertukaran budaya di mana Inggris dan orang Indonesia belajar tentang etiket, pakaian, dan seni masing-masing.
Salah satu inisiatif budaya konkret adalah revitalisasi Kebun Raya Bogor (Buitenzorg). Sementara kebun telah ada sejak 1744 di bawah Belanda, Raffles mengambil minat yang tajam dalam botani dan membuat kebun dirancang dalam gaya Inggris. Ia mengimpor spesies tanaman baru dan mengkatalog flora Jawa, menyiapkan panggung untuk apa yang akan menjadi pusat penelitian botani utama di bawah manajemen Belanda kemudian.
Selain itu, Raffles terlibat dalam mendirikan apa yang kemudian menjadi Masyarakat Sastra Jawa, pada dasarnya mendorong lingkaran ilmiah di Batavia untuk mempelajari budaya lokal (ini diformalkan oleh Belanda pada tahun 1820 sebagai Masyarakat Seni dan Sains Batavia, tetapi memiliki akar di masa Raffles).
Dalam hal agama, Inggris tidak melakukan upaya signifikan untuk mengubah lanskap religius. Raffles, meskipun secara pribadi seorang Kristen, tidak mensponsori aktivitas misionaris Kristen di Jawa (tidak seperti di beberapa koloni Inggris). Ia menghormati peran Islam dalam masyarakat Jawa dan bahkan menunjukkan minat dalam yurisprudensi Islam karena itu mempengaruhi kepemilikan tanah.
Ada satu perubahan yang menonjol: Inggris menghapus beberapa pembatasan yang dimiliki Belanda pada ziarah ke Mekah. VOC telah mencoba mengendalikan ketat atau melarang ziarah Haji karena takut akan ide-ide radikal; Inggris lebih laissez-faire, yang memungkinkan beberapa orang Jawa untuk melakukan ziarah selama pemerintahan Inggris. Ini dapat dilihat sebagai pembukaan budaya kecil.
Di Maluku, Inggris, yang Protestan seperti Belanda, sebagian besar meninggalkan komunitas Kristen sebagaimana adanya, dan tidak campur tangan dengan praktik religius lokal selain memastikan kebebasan beribadah.
Pendidikan dan Media
Administrasi Inggris membuat langkah awal menuju penyediaan pendidikan, meskipun tidak ada yang bertahan lama yang didirikan. Raffles membahas rencana untuk perguruan tinggi di Jawa untuk mendidik putra-putra bangsawan Jawa dalam pengetahuan dan bahasa modern, tetapi ini tidak terwujud sebelum penyerahan.
Namun demikian, dengan mengekspos elit Indonesia pada ide-ide Inggris, benih perspektif baru ditaburkan. Beberapa aristokrat Jawa melakukan perjalanan ke Kalkuta dengan tim Raffles dan terpapar masyarakat kolonial Inggris-India. Sebaliknya, banyak perwira Inggris belajar Melayu atau sedikit Jawa, mendorong pertukaran linguistik.
Adapun media, Inggris mencetak berita dan pemberitahuan pemerintah di Batavia dalam berbagai bahasa (Inggris, Melayu, dan Belanda) untuk menjangkau audiens yang berbeda. Ini mungkin dianggap sebagai prekursor pers kolonial multibahasa, meskipun pers berkelanjutan dalam bahasa Indonesia hanya akan datang kemudian di bawah Belanda.
Warisan dan Pengaruh Budaya yang Bertahan
Periode kolonial Inggris di Indonesia singkat, jadi jejak langsung pada budaya Indonesia modern tidak besar. Pengaruh Belanda, yang lebih dari tiga abad lamanya, dipahami dapat dimengerti mengaburkan kontribusi Inggris. Misalnya, tidak seperti Malaysia atau India di mana bahasa Inggris menjadi berakar, di Indonesia bahasa Belanda dan, kemudian, Indonesia (Melayu) tetap menjadi bahasa kolonial dan nasional utama.
Hanya segelintir kata pinjaman Inggris yang masuk ke dalam bahasa Indonesia pada tanggal awal itu. Satu warisan abadi adalah nama Indonesia itu sendiri, yang menarik diciptakan oleh etnolog Inggris, George Windsor Earl, dan dipopulerkan oleh James Richardson Logan (seorang Inggris) pada tahun 1850.
Istilah ini kemudian diadopsi oleh nasionalis sebagai nama negara merdeka. Dengan demikian, beasiswa Inggris secara tidak langsung berkontribusi pada konsep identitas nasional Indonesia (dengan mengidentifikasi Nusantara sebagai wilayah budaya yang berbeda).
Upaya Inggris dalam melestarikan barang antik Jawa telah memiliki dampak yang bertahan lama. Penemuan Borobudur pada tahun 1814 oleh Inggris membawanya ke perhatian dunia. Selanjutnya, pemerintah Belanda dan kemudian Indonesia mengambil langkah-langkah untuk melestarikan dan mengembalikan monumen ini, yang saat ini merupakan situs Warisan Dunia UNESCO dan sumber kebanggaan nasional.
Bisa dibilang, Raffles menetapkan proses itu dengan membersihkan situs. Banyak artefak dan manuskrip yang diambil oleh Raffles dan lainnya berakhir di lembaga Inggris (seperti British Museum atau Perpustakaan Kantor India). Sementara kerugian ini disesalkan di Indonesia, artefak-artefak itu memang memainkan peran dalam memperkenalkan budaya Indonesia ke Eropa.
Wayang kulit Jawa, instrumen gamelan, patung candi, dan spesimen botani dipamerkan di London pada abad ke-19, memicu minat Eropa pada warisan Indonesia.
Secara sosial, seseorang dapat mengatakan periode Inggris menawarkan orang Indonesia sekilas kebijakan kolonial alternatif, yang mengaku ideal yang lebih liberal dan manusiawi. Ini tidak langsung diterjemahkan menjadi perubahan di lapangan setelah 1816, tetapi generasi Indonesia kemudian mengingat Raffles dengan warna yang agak positif.
Dalam historiografi Indonesia, Raffles kadang-kadang dikreditkan karena relatif tercerahkan (misalnya, untuk menghapuskan perbudakan dan menulis tentang kebesaran Jawa). Ini telah mempengaruhi memori budaya Indonesia; Raffles muncul sebagai tokoh simpatik di beberapa buku teks Indonesia, yang langka di antara administrator kolonial.
Periode ini juga secara tidak langsung mendorong rasa kebanggaan Jawa: dengan mendokumentasikan reruntuhan Majapahit dan raja-raja kuno, karya Raffles History of Java membantu intelektual Jawa di akhir abad ke-19 menemukan kembali kejayaan masa lalu mereka sendiri, memicu kebanggaan proto-nasionalis dalam pencapaian pra-kolonial.
Kesimpulannya, sementara singkat, interlude Inggris di Indonesia memfasilitasi pertukaran budaya yang bermakna: beasiswa, pelestarian artefak, studi linguistik, dan reformasi sosial kecil. Warisan abadi termasuk kontribusi pada catatan sejarah dan budaya Indonesia (melalui buku dan artefak), langkah-langkah abolisionis awal, dan menetapkan contoh (betapapun ephemeral) bahwa pemerintahan kolonial bisa kurang eksploitatif.
Banyak inisiatif budaya dan sosial Raffles lebih maju dari zamannya, dan beberapa hanya akan sepenuhnya dihargai atau diterapkan dalam beberapa dekade berikutnya dalam keadaan yang berbeda. Keterbukaan budaya dan rasa ingin tahu yang ditunjukkan oleh Inggris selama tahun 1811-1816 sedikit kontras dengan pendekatan Belanda yang lebih ekstraktif dari era itu, meninggalkan kesan bahwa kolonisasi tidak perlu sepenuhnya mengabaikan nilai budaya lokal.
Analisis Geografis Pengaruh Inggris
Wilayah Inti Aktivitas Inggris
Geografi keterlibatan Inggris di Indonesia bersifat selektif. Fokus utama adalah pulau Jawa, jantung politik dan ekonomi Hindia Timur Belanda. Jawa mengalami dampak Inggris yang paling mendalam, di mana Raffles memerintah dan mereformasi, di mana pasukan Inggris terkonsentrasi, dan di mana peristiwa seperti serangan Yogyakarta terjadi.
Area kunci di Jawa termasuk Batavia (Jakarta) di pantai barat laut, yang berfungsi sebagai ibu kota administratif di bawah Inggris seperti di bawah Belanda. Buitenzorg (Bogor) di dekatnya adalah kediaman negara Raffles dan pusat aktivitas botani dan administratif. Di Jawa Tengah, kota-kota kerajaan Yogyakarta dan Surakarta signifikan: Yogyakarta menghadapi intervensi Inggris langsung (penjarahan tahun 1812), sedangkan Surakarta bekerja sama dan sebagian besar menghindari konflik, tetapi kedua istana berinteraksi dengan residen Inggris.
Pelabuhan Pantai Utara Jawa (Semarang, Rembang, Surabaya, dll.) juga berada di bawah pengawasan Inggris, karena ini penting untuk perdagangan. Pejabat Inggris mengambil alih residensi pelabuhan ini untuk memastikan aliran pendapatan dan ketertiban.
Di luar Jawa, pulau Sumatra memiliki kantong pengaruh Inggris. Wilayah Inggris yang sudah lama Bencoolen (Bengkulu) di pantai barat daya Sumatra adalah kepemilikan Inggris sepanjang periode ini (dan memang sejak 1685 hingga 1824). Bencoolen dan pedalaman (kadang-kadang disebut Residensi Bencoolen) diatur terpisah dari Jawa.
Sementara Jawa berada di bawah Perusahaan Hindia Timur selama tahun 1811-16, Bencoolen secara teknis berada di bawah Kepresidenan Bengal EIC dan kemudian diawasi langsung oleh Raffles juga. Ekspedisi Inggris ke Palembang di Sumatra timur juga menandai wilayah itu. Palembang dan pulau Bangka jatuh di bawah kendali Inggris sementara sekitar tahun 1812-1813.
Meskipun Inggris tidak secara resmi mencaplok Palembang (mereka meninggalkan sultan baru yang bertanggung jawab), mereka menduduki pulau Bangka, memperlakukannya hampir seperti pos Inggris sampai diserahkan kepada Belanda pada tahun 1816-1817. Di Sumatra utara, Inggris telah mendirikan pos kecil sebelumnya (seperti di Natal dan Tapanuli di pantai barat) selama akhir abad ke-18 untuk mengumpulkan lada, tetapi ini kecil.
Yang penting, kehadiran Inggris di Sumatra terfragmentasi: pantai barat (Bengkulu), tenggara (Palembang/Bangka), dan tidak seluruh pulau. Bagian besar Sumatra, seperti Aceh di ujung utara dan dataran tinggi Minangkabau di barat, tetap independen dari Inggris dan Belanda selama waktu ini.
Di Indonesia timur, pulau-pulau Maluku adalah titik fokus lainnya. Inggris mengendalikan pulau-pulau penghasil rempah-rempah utama: Ambon, Kepulauan Banda (terutama Banda Neira/Run), dan Ternate/Tidore di Maluku Utara. Mereka telah menangkap ini pada tahun 1810 dan menahannya sampai tahun 1817.
Ambon secara administratif signifikan (mantan gubernur VOC Ambon digantikan oleh Residen Inggris). Kepulauan Banda langsung dikelola oleh komandan Inggris yang mengawasi perkebunan pala, termasuk memperkenalkan perdagangan yang lebih bebas dan mengakhiri sistem perbudakan dan kerja budak Belanda di perkebunan pala tersebut.
Di Ternate, Inggris bekerja sama dengan Sultan Ternate, pada dasarnya mewarisi perjanjian Belanda. Maluku dengan demikian melihat kehadiran militer dan administratif Inggris, tetapi tidak seperti Jawa, mereka tidak mencoba reformasi menyeluruh di sana; mereka puas menjaga perdamaian dan mengeksploitasi rempah-rempah.
Masyarakat lokal (sebagian besar orang Ambon Kristen dan penduduk pulau Muslim) melihat perubahan struktural yang lebih sedikit di bawah Inggris, selain liberalisasi perdagangan.
Selain itu, Inggris sempat mengambil kendali kepemilikan Belanda yang tersisa lainnya: misalnya, Makassar di Sulawesi (Celebes). Selama Perang Napoleon, benteng Belanda di Makassar (Benteng Rotterdam) menyerah kepada Inggris (sekitar tahun 1811). Makassar adalah pelabuhan penting dan Inggris kemungkinan menempatkannya di bawah Residen juga.
Namun, pengaruh Inggris di Sulawesi minimal dalam hal mengubah pemerintahan lokal: bangsawan Bugis dan Makassar terus menjalankan urusan lokal, dan Inggris hanya seorang penguasa jauh selama beberapa tahun. Demikian pula, Borneo (Kalimantan) memiliki pijakan Belanda di Banjarmasin dan Pontianak; ini secara nominal dipindahkan ke pengawasan Inggris selama tahun 1811-16.
Ada sedikit bukti bahwa Inggris melakukan banyak hal di Borneo selain mempertahankan kehadiran. Sultan lokal (seperti Sultan Banjar) tetap berkuasa dengan pengakuan Inggris. Inggris direntang tipis dan memprioritaskan Jawa dan Maluku, jadi Borneo dan pulau-pulau lain melihat kesinambungan daripada perubahan selama interregnum.
Variasi Regional dalam Pengaruh Inggris
Intensitas dan sifat pengaruh Inggris bervariasi menurut wilayah. Jawa adalah pusat reformasi dan pengaruh Inggris. Di sini, administrasi Inggris komprehensif: mereka menerapkan sistem sewa tanah baru, mereorganisasi distrik, terlibat dalam pekerjaan umum (pemeliharaan Jalan Pos Besar yang dibangun Daendels, misalnya), dan menyelidiki urusan budaya (penggalian arkeologi, pendirian perpustakaan).
Jawa melihat pemerintahan langsung oleh Inggris, jadi jejak kebijakan Inggris (administratif dan ekonomi) paling dalam di sini. Secara sosial, masyarakat Jawa di tingkat elit berinteraksi dengan Inggris; rakyat jelata Jawa juga secara langsung dipengaruhi oleh pergeseran kebijakan dalam perpajakan dan tenaga kerja.
Di Sumatra, pengaruh Inggris tidak merata. Di Bencoolen, pemerintahan Inggris sudah berlangsung lama tetapi daerahnya relatif kecil dan terisolasi. Dampak di sana menonjol karena Raffles (sebagai gubernur setelah 1818) membebaskan budak dan mencoba meningkatkan ekonominya. Namun, Bencoolen kurang berkembang secara ekonomis dan secara politis marginal (sering digambarkan sebagai pos lada pedalaman).
Di Palembang dan Bangka, Inggris hanya tinggal beberapa tahun; mereka menggulingkan penguasa, lalu menyerahkan wilayah ke Belanda. Pengaruh utama adalah penghapusan singkat cengkeraman monopolistik Belanda pada perdagangan timah dan lada, memberi penduduk lokal rasa pemerintahan yang berbeda.
Aceh, di utara Sumatra, tetap independen tetapi Inggris memiliki perjanjian dengannya (pada tahun 1819, Raffles menandatangani perjanjian dengan Aceh untuk menjamin kemerdekaannya sebagai penyangga terhadap ekspansi Belanda). Perjanjian ini kemudian mempengaruhi pengaturan Anglo-Belanda dan menunda penaklukan Belanda atas Aceh. Jadi secara tidak langsung, diplomasi Inggris membentuk geografi politik Sumatra (kedaulatan berkelanjutan Aceh) sampai akhir abad ke-19.
Di Maluku, pengaruh Inggris sebagian besar bersifat komersial dan militer. Inggris membongkar monopoli cengkeh dan pala Belanda dan mengizinkan petani rempah-rempah lebih banyak kebebasan (meskipun banyak perkebunan di Banda sebenarnya dikerjakan oleh budak atau tenaga kerja kontrak: Inggris tidak membebaskan mereka di Banda selama pendudukan).
Pulau Run yang terkenal di Banda, yang telah didambakan Inggris sejak abad ke-17, berada di bawah kendali mereka pada tahun 1810-an; seperti dicatat, mereka mengambil tanaman pala dari sana untuk menyebarkan di tempat lain. Secara budaya, pengaruh Inggris di Maluku termasuk kontak mereka dengan komunitas Kristen (Ambon), yang menemukan Inggris umumnya toleran terhadap iman mereka dan bahkan bergantung pada mereka sebagai sekutu (banyak pria Ambon bergabung dengan pasukan Inggris).
Ini mungkin memperkuat rasa loyalitas Ambon kepada siapa pun yang memperlakukan mereka dengan baik, ironis, ini berkontribusi pada pemberontakan tahun 1817 ketika kembalinya Belanda mengancam untuk mengembalikan beban. Tetapi secara keseluruhan, perubahan pemerintahan Inggris (seperti sewa tanah) tidak diterapkan di Maluku, yang dibiarkan di bawah sistem tradisional selain perdagangan.
Pulau-pulau lain (Borneo, Sulawesi, Bali, dll.) kehadiran Inggris sebagian besar nominal. Mereka mengirim utusan ke Bali. Raffles mengunjungi Bali pada tahun 1815 dan menjalin hubungan persahabatan dengan raja-raja Bali, bahkan mengamankan pengembalian meriam perunggu Narayana ke Bali yang telah disita Belanda sebelumnya (isyarat itikad baik). Tetapi tidak ada administrasi yang didirikan di Bali; itu tetap di luar kendali kolonial langsung sampai jauh kemudian (oleh Belanda).
Di Borneo, pengaruh Inggris marginal, meskipun menarik, beberapa dekade kemudian (1840-an), Inggris akan secara tidak langsung kembali melalui Sir James Brooke di Borneo Utara, tetapi itu terpisah dari peristiwa tahun 1811-16.
Singkatnya, ruang lingkup geografis pemerintahan Inggris di Indonesia luas di atas kertas (sebagian besar bekas Hindia Timur Belanda), tetapi dalam praktiknya intensitas bervariasi. Jawa dikelola dan direformasi secara menyeluruh; Sumatra dan Maluku dipegang karena alasan strategis dan melihat intervensi selektif; banyak pulau luar mengalami sentuhan Inggris yang ringan karena kerangka waktu singkat dan sumber daya terbatas.
Warisan Regional
Akibatnya juga berbeda menurut wilayah. Jawa, setelah tahun 1816, sebagian besar kembali ke sistem Belanda, tetapi beberapa divisi administratif Raffles (Residensi) tetap menjadi dasar divisi masa depan. Gagasan pajak tanah muncul kembali kemudian dalam bentuk modifikasi setelah akhir Sistem Kultuur, menunjukkan Jawa membawa pengaruh konsep itu.
Di Sumatra, keberangkatan Inggris pada tahun 1824 berarti seluruh pulau jatuh ke Belanda, kecuali Aceh. Dukungan Inggris atas kemerdekaan Aceh (melalui perjanjian) secara tidak langsung menetapkan panggung untuk perlawanan Aceh yang berlarut-larut terhadap Belanda (1873-1904).
Di Maluku, warisan utama pemerintahan Inggris adalah penyebaran tanaman rempah-rempah; secara ekonomis, Maluku tidak pernah mendapatkan kembali kepentingan abad ke-17 setelah cengkeh dan pala tumbuh di koloni lain. Secara budaya, Maluku mengingat pemberontakan Pattimura (yang pada dasarnya merupakan reaksi untuk kehilangan interregnum Inggris yang relatif lebih bebas).
Pembagian wilayah pada tahun 1824 memiliki dampak geografis yang bertahan lama: itu menarik garis melalui Nusantara Melayu, dengan Malaya Inggris dan Borneo Utara di satu sisi dan Hindia Timur Belanda di sisi lain. Inilah mengapa Malaysia dan Singapura hari ini berbahasa Inggris (dipengaruhi Inggris) sementara Indonesia berbahasa Belanda selama era kolonial.
Pembagian geopolitik itu adalah hasil langsung dari periode Inggris dan negosiasi berikutnya. Ini mempengaruhi migrasi, rute perdagangan, dan bahkan afinitas budaya (misalnya, Semenanjung Melayu berkembang secara berbeda dari Sumatra tepat di seberang Selat Malaka karena berada di bawah wilayah kolonial terpisah).
Kesimpulannya, secara geografis periode kolonial Inggris di Indonesia terkonsentrasi di pusat ekonomi dan politik kunci (Jawa, pulau-pulau rempah-rempah, pelabuhan Sumatra tertentu), meninggalkan pengaruh tambal sulam. Jawa, sebagai permata koloni, mengalami perubahan yang paling signifikan yang didorong Inggris, sedangkan wilayah yang lebih periferal melihat intervensi langsung yang relatif kecil.
Variasi regional menyoroti bahwa pemerintahan Inggris tidak seragam di seluruh Nusantara: itu berkisar dari pemerintahan komprehensif di Jawa hingga sekadar pengasuhan di pulau-pulau yang jauh, tetapi secara kolektif, itu menyentuh banyak bagian dari apa yang sekarang Indonesia, jika hanya sebentar, selama interval awal abad ke-19 itu.
Kesimpulan
Ketika kita merenungkan periode kolonial Inggris di Indonesia, yang hanya berlangsung lima tahun namun penuh dengan perubahan dan eksperimen, kita melihat sebuah interlude sejarah yang unik dan sering terlupakan. Periode ini bukan sekadar catatan kaki dalam kisah panjang kolonialisme di Nusantara, melainkan momen penting yang membawa ide-ide baru, reformasi berani, dan warisan yang masih bergema hingga hari ini.
Di bawah kepemimpinan Thomas Stamford Raffles yang visioner meski kontroversial, Indonesia mengalami percobaan dengan pemerintahan kolonial yang lebih liberal dan tercerahkan. Penghapusan kerja paksa, pengenalan sistem pajak tanah yang lebih manusiawi, pelonggaran pembatasan perdagangan, dan upaya untuk mengurangi penindasan feodal merupakan langkah-langkah radikal pada masanya. Meskipun banyak reformasi ini tidak bertahan lama setelah Belanda kembali, mereka menanam benih ide yang akan berkecambah di kemudian hari.
Kontribusi budaya periode Inggris juga tidak dapat diabaikan. Penggalian Borobudur, pelestarian manuskrip Jawa, studi mendalam tentang bahasa dan budaya lokal, dan bahkan penciptaan nama "Indonesia" itu sendiri, semuanya merupakan warisan yang bertahan dari lima tahun singkat ini. Raffles dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa pemerintahan kolonial dapat disertai dengan rasa hormat terhadap dan rasa ingin tahu tentang budaya lokal, meskipun motif mereka tetap imperial.
Dari perspektif militer, periode Inggris relatif kurang berdarah dibandingkan dengan banyak konflik kolonial berikutnya. Serangan brutal di Yogyakarta menjadi pengecualian daripada aturan. Pendekatan Inggris yang lebih moderat (meski masih kolonial) meninggalkan kesan yang berbeda dibandingkan dengan kampanye Belanda yang panjang dan brutal atau pendudukan Jepang yang mengerikan kemudian.
Secara ekonomi, meskipun kebijakan perdagangan bebas Inggris tidak menghasilkan keuntungan langsung yang diharapkan EIC, mereka membuka Nusantara ke jaringan perdagangan global yang lebih luas dan memecahkan monopoli Belanda yang telah berlangsung berabad-abad. Penyebaran tanaman rempah-rempah Indonesia ke seluruh dunia selama periode ini mengubah ekonomi global secara permanen.
Hari ini, ketika saya berdiri di Bogor dan melihat Kebun Raya yang indah, atau ketika saya membaca tentang Borobudur yang megah, atau ketika saya mendengar nama negara kita sendiri, "Indonesia", saya tidak bisa tidak teringat pada periode singkat namun penting ini. Interlude Inggris di Indonesia adalah pengingat bahwa sejarah sering dibentuk oleh momen-momen singkat sebanyak oleh era yang panjang.
Ini adalah kisah tentang apa yang bisa terjadi, kesempatan yang diambil dan hilang, dan eksperimen yang terlalu singkat untuk sepenuhnya direalisasikan tetapi cukup lama untuk meninggalkan jejak yang tidak dapat dihapuskan. Periode kolonial Inggris di Indonesia mungkin hanya sebuah interlude, tetapi itu adalah interlude yang layak diingat, dipelajari, dan dipahami sebagai bagian integral dari perjalanan kompleks Indonesia menuju nasion modern yang kita kenal sekarang.

